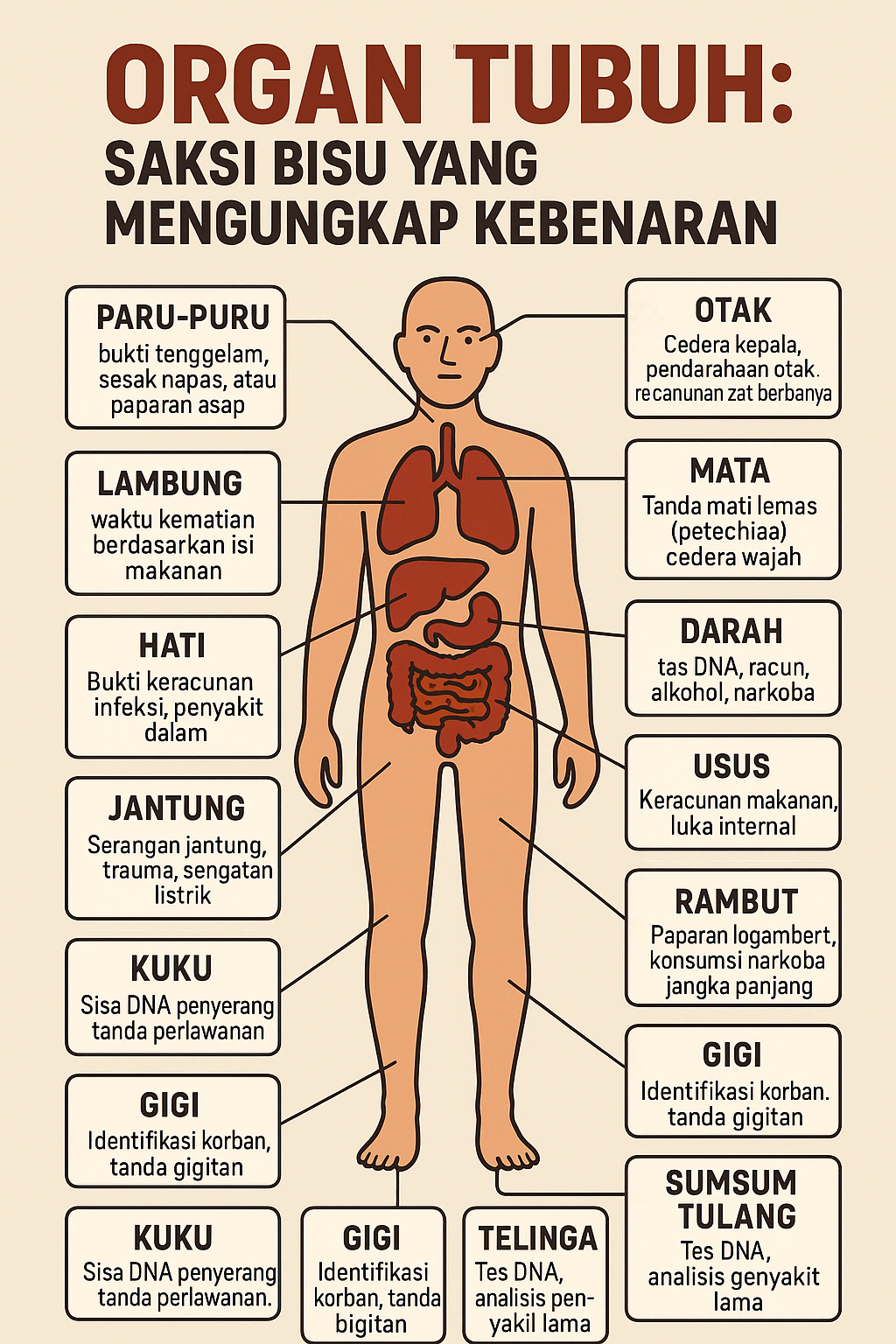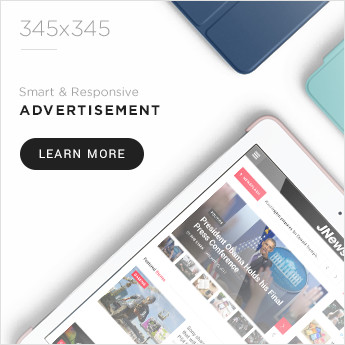Chapter 1 :
Di kepala Petruk, negara itu bukan sekadar wilayah yang diapit pulau, dibatasi garis khatulistiwa, dan dihiasi lambang burung garuda. Negara itu bukan gedung megah berkubah emas yang dijaga pagar besi tinggi. Bukan pula deretan mobil dinas yang disemprot disinfektan dan diparkir berjajar di halaman balai kota.
Bagi Petruk, negara itu sederhana: bisa nggak rakyat makan tiga kali sehari tanpa harus mencicil bumbu dapur ke warung? Bisa nggak seorang ibu menyajikan sarapan untuk anak-anaknya tanpa harus menimbang antara beli beras atau bayar listrik?
“Negara itu ya semestinya kayak ibu di dapur,” kata Petruk sambil menyendok sayur lodeh ke piring seng yang pinggirannya sudah karatan. “Bukan cuma tahu siapa yang lapar, tapi juga tahu siapa yang pura-pura kenyang demi adiknya.”
Petruk memang bukan ahli ekonomi, bukan pejabat, dan tak pernah jadi narasumber di podcast politik. Tapi Petruk tahu betul: kalau harga cabai naik, ibu-ibu pasar jadi sensitif. Kalau minyak goreng langka, emosi warga jadi pendek. Dan kalau gas melon hilang dari pasaran, dapur rakyat bisa mati—bersama harapan dan doa-doa.
Di televisi, para elite bicara tentang pertumbuhan ekonomi, soal angka-angka yang katanya naik. Tapi Petruk menatap isi kulkas rumah tetangganya: kosong. Bahkan sayur bayam pun kini terasa mewah. Di mata rakyat kecil, ekonomi bukan grafik yang menanjak, tapi nasi yang bisa ditanak.
“Lha gimana mau percaya sama pemerintah, Gareng,” kata Petruk suatu malam, “wong kita dikasih bansos, tapi harga kebutuhan pokok malah naik diam-diam.”
Ia sering merasa janggal: kenapa negara seolah lebih sibuk membangun jembatan tol ke kawasan industri daripada membangun kepercayaan di hati rakyat? Kenapa gembar-gembor megaproyek lebih ramai daripada kabar tentang ibu-ibu yang antre beras murah?
Petruk percaya, pembangunan bukan soal beton dan baja. Tapi soal hati yang terjaga. Soal dapur yang tetap hangat meski gaji pas-pasan. Soal anak-anak bisa sekolah tanpa harus menunggu tanggal muda. Negara yang baik bukan yang banyak peresmian, tapi yang rakyatnya tak perlu antre kupon untuk hidup layak.
Di kepala Petruk, negara adalah ruang makan bersama. Tempat di mana semua orang duduk setara. Pemimpin bukan yang duduk di ujung meja, tapi yang mengambilkan nasi untuk yang tertinggal.
“Kamu tahu, Gareng?” kata Petruk, mengelus jenggot tipisnya. “Kalau negara hanya sibuk menghitung proyek dan lupa menghitung piring kosong di rumah-rumah rakyat, itu bukan pembangunan. Itu penelantaran.”
Ia ingat betul, neneknya dulu bilang: kalau kamu ingin tahu kualitas sebuah rumah tangga, lihat dapurnya. Dan jika ingin tahu kualitas sebuah negara, lihat isi piring rakyatnya.
Karena dapur bukan sekadar tempat masak. Ia adalah pusat kehidupan. Tempat perut diisi, hati disapa, dan masa depan direncanakan. Jika dapur rakyat sepi, negara pun akan sepi makna.
Petruk bukan anti kemajuan. Ia suka jalan tol, ia juga bangga kalau Indonesia punya bandara mewah. Tapi yang ia minta sederhana: jangan biarkan rakyat kehilangan api di tungku karena terlalu sibuk membangun menara.
Dan dalam kepala Petruk yang sederhana, tapi tajam dan jernih, satu pesan mengendap dalam-dalam:
Negara yang gagal mengurus dapur rakyatnya, pelan-pelan akan kehilangan tempat di hati warganya.
Itulah sebabnya, Petruk selalu bilang, “Jangan bangun negara dari atas. Bangunlah dari dapur.”