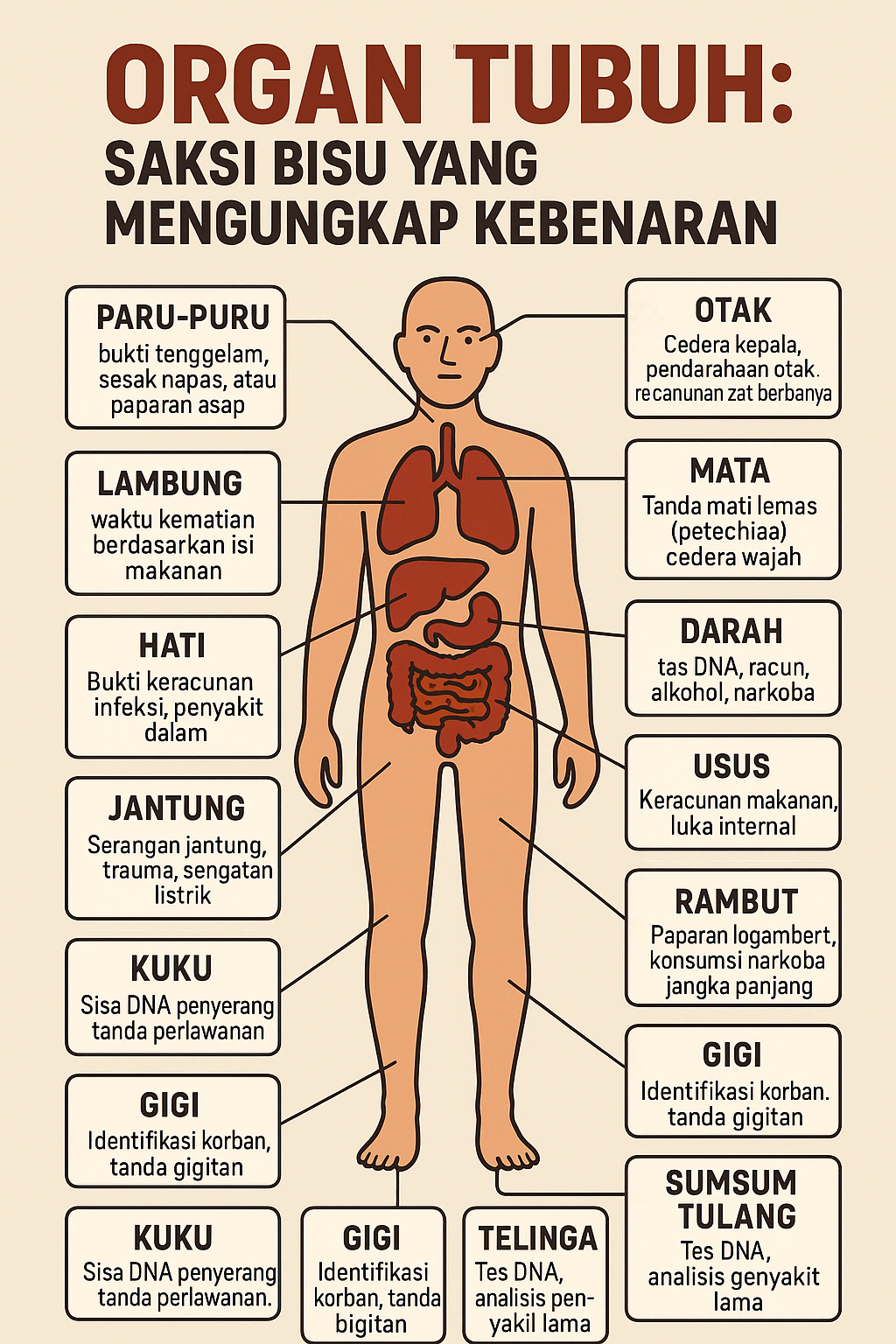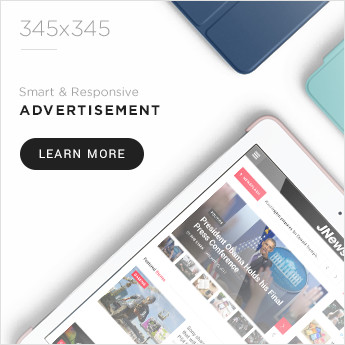Oleh: Arfian Dikron Septiandri – Mahasiswa Fakultas Hukum UMT Cipinang Jakarta Timur
“Hukum itu bukan kitab suci. Kadang isinya suci, kadang juga penuh drama manusiawi.”
– Penulis, waktu lagi kesel liat sidang digoreng-goreng
Yo, para pejuang toga dan netizen kritis yang hobi nyinyir pake data!
Kali ini kita bahas topik yang agak berat, tapi dibikin light, biar otak nggak ngehang kayak aplikasi belajar pas jam 3 pagi.
Judulnya: Antropologi Yurisprudensi.
Eh, jangan kabur dulu. Emang sih, kedengerannya kayak mantra Latin dari film Harry Potter, tapi ini penting banget buat kita yang hidup di negeri +62 ini—yang sistem hukumnya kadang kayak WiFi gratisan: ada, tapi susah nyambungnya.
Hukum Itu Bukan Robot, Bro!
Gini ya, hukum di Indonesia itu nggak hidup di ruang vakum. Dia hidup di tengah masyarakat yang plural, dari Sabang sampai Merauke, dari adat yang sakral sampai gosip yang viral. Jadi jangan heran kalau satu pasal bisa ditafsir beda-beda, tergantung siapa yang bacanya dan sedang melayani kepentingan siapa.
Nah, di sinilah antropologi yurisprudensi masuk. Ini tuh semacam kacamata kuda versi open-minded. Dia ngajarin kita buat nggak cuma ngeliat hukum dari teks undang-undang, tapi juga dari konteks budaya, adat, dan sejarah masyarakat.
Karena, percayalah, kadang hukum itu lebih cocok dibaca dengan hati daripada dengan palu hakim.
Kearifan Lokal vs Kegarangan Global
Contoh nih ya, ada sengketa tanah di kampung. Warga minta diselesaikan pakai adat—musyawarah, mediasi, ngopi dulu. Tapi si aparat langsung bawa surat resmi, bahasa hukum yang bikin kepala ngebul, dan ngancem pakai pasal. Lah, jadinya nggak ketemu. Karena satu pihak pakai logika, satu pihak pakai rasa.
Antropologi yurisprudensi ngajarin kita: “Eh, sob, hukum itu harus nyambung sama budaya lokal. Jangan mentang-mentang berjas, jadi lupa akar rumput.”
Hukum vs Keadilan: Kadang Nggak Satu Frekuensi
Ini yang paling nyesek. Banyak kasus di mana hukum ditegakkan, tapi rasa keadilan malah tumbang. Yang salah bisa bebas karena celah pasal, yang bener malah dibikin kalah karena nggak ngerti prosedur. Ujung-ujungnya, rakyat bilang, “hukum cuma buat yang punya duit dan kuasa.”
Penulis pun geleng-geleng, “Hukum kok kayak sinetron, penuh plot twist dan tangisan?”
Makanya, kalau kamu anak hukum, jangan jadi kaku kayak beton. Pelajari juga nilai-nilai budaya dan sosial. Karena hukum yang nggak ngerti masyarakatnya, itu kayak Google Maps di tengah hutan adat—nyasar, bro!
Harapan dari Mahasiswa Hukum (Yang Belum Lulus-Lulus)
Gue nulis ini bukan karena sok tahu. Tapi karena masih punya harapan. Harapan bahwa hukum di negeri ini suatu hari nggak cuma dipakai buat ngelindungi yang kuat, tapi juga ngebela yang lemah. Nggak cuma soal menang-kalah, tapi soal ngerti konteks dan rasa.
Jadi, wahai aparat, pejabat, mahasiswa, dan netizen budiman…
Belajarlah hukum dari rakyat, bukan cuma dari bangku kuliah.
Karena hukum itu bukan sekadar bunyi palu, tapi suara hati nurani bangsa.
Penulis Says:
“Kalau kamu kuliah hukum tapi nggak ngerti realita sosial, ya sama aja kayak ngapalin lirik lagu yang salah genre.”
Penulis Adds:
“Dan jangan lupa… kadang hukum yang adil bukan yang keras, tapi yang nyambung sama nurani rakyat.”