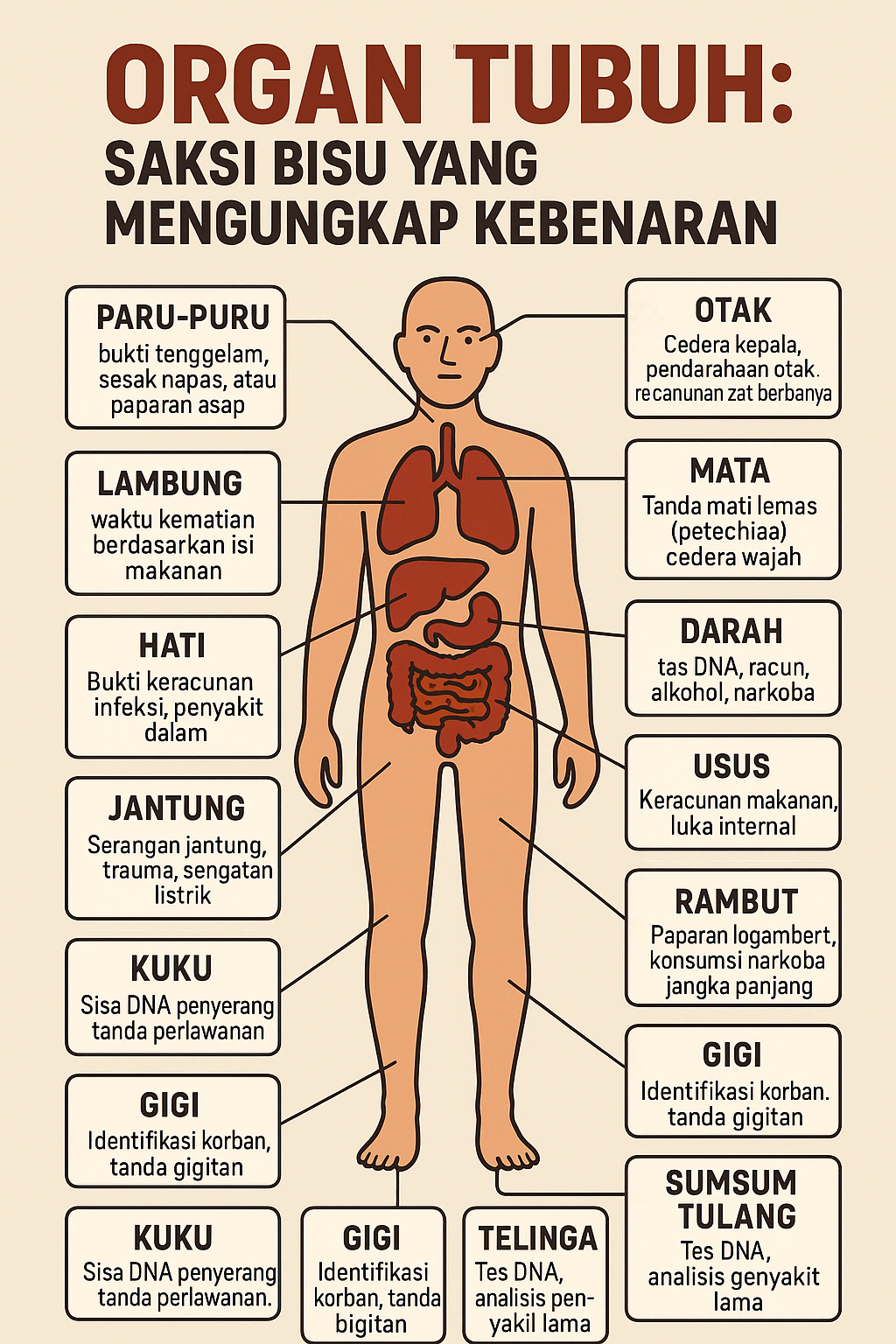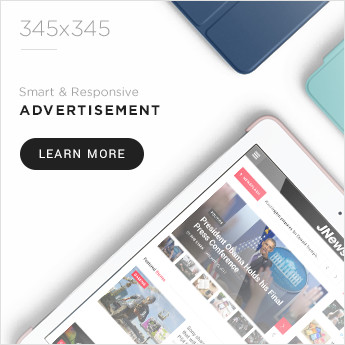Di tengah riuh rendah janji-janji manis yang dijual para pemimpin seperti gorengan di pinggir jalan—gurih di awal, kolesterol di akhir—tinggallah satu sosok yang tak lagi percaya lidah manusia: Penyair Bisu.
Dia tidak bersajak dengan tinta emas, tidak pula berpantun dengan mikrofon mahal. Ia bersyair lewat mata yang sembab, napas yang berat, dan diam yang menggigilkan makna. Kata-katanya bukan dibentuk dari kamus besar bahasa negara, tapi dari derita rakyat yang panjang tak berkesudahan. Kadang sedih, kadang bahagia, kadang… ya ampun, melantur tak tentu arah, kayak janji kampanye.
“Kami ini rakyat,” kata sang Penyair Bisu dalam diamnya.
“Kami bukan butuh dikasihani, kami hanya butuh didengarkan—bukan dikibuli!”
Dari Derita Menjadi Doa
Penyair ini bukan siapa-siapa. Tak punya panggung di televisi, tak dipanggil ke istana, apalagi masuk FYP. Tapi dalam setiap lirih napasnya, ada doa yang naik ke langit dan gugur ke bumi sebagai air mata.
Ia begitu merindukan Tuhan.
Bukan karena ia alim,
tapi karena Tuhan satu-satunya yang belum berbohong padanya.
“Pemimpin datang silih berganti,” katanya suatu kali, sambil menatap langit yang mendungnya seperti nasib rakyat kecil.
“Tapi nasib kami tetap di bawah—di bawah janji, di bawah meja, bahkan di bawah garis kemiskinan.”
Ketika Kursi Lebih Berkuasa dari Nurani
Penyair Bisu hanya ingin bersuara. Tapi bukan dengan teriak. Suaranya ingin seperti angin—yang lembut tapi bisa merobohkan kursi-kursi para koruptor. Angin yang meniup lembar-lembar kontrak fiktif, yang membalik meja-meja rapat penuh dusta, yang menyapu bersih senyum palsu para elite yang menganggap rakyat hanya angka statistik.
“Keadilan,” katanya,
“dulu kami minta dengan penuh harap. Sekarang kami cuma bisa menatap,
sebab yang datang bukan keadilan, tapi penderitaan yang makin rapi berjas dan berdasi.”
Penyair Tak Bernama, Tapi Bernyawa
Mereka tak muncul di berita.
Tak punya akun centang biru.
Tapi mereka adalah penyair-penyair bisu yang hidup di kolong jembatan, di sawah yang kering, di pabrik yang ditutup, dan di sekolah yang roboh. Mereka menulis puisi dengan lapar, membaca dengan air mata, dan mencintai negeri ini tanpa syarat—bahkan ketika negeri ini mencintai mereka setengah hati.
Sarkasme dari Sunyi
Lucunya, di negeri yang katanya demokrasi ini, suara rakyat justru dituduh makar. Demonstrasi dituduh provokasi. Kritik dianggap delik. Dan bisu—ternyata adalah pilihan paling aman untuk tetap hidup.
Penyair Bisu tidak meminta panggung.
Ia hanya ingin hidup tanpa harus dibohongi.
Ia tidak ingin jadi pahlawan.
Ia hanya ingin tidak jadi korban.
Diam yang Membunuh atau Membebaskan?
Lalu, siapa yang mendengar para penyair bisu itu?
Mungkin tidak ada.
Mungkin hanya Tuhan.
Atau mungkin… angin.
Angin yang akan datang membawa pesan,
menerbangkan sajak diam,
menghempaskan kursi-kursi kekuasaan yang dibangun di atas kebohongan.
“Kami mungkin bisu,” kata mereka.
“Tapi kami tak akan selamanya diam. Sebab angin pun bisa menjadi badai.”
#PenyairBisu
#SajakRakyat
#AnginPenggulingTahta
#JanjiAdalahInflasiKata
#GarengPetrukBersuara
“Rakyat adalah puisi panjang yang sering disensor, tapi tak bisa dibungkam.” – Gareng
Kalau sampean suka, viralkan. Kalau sampean tersindir, maaf… berarti itu memang buat sampean.