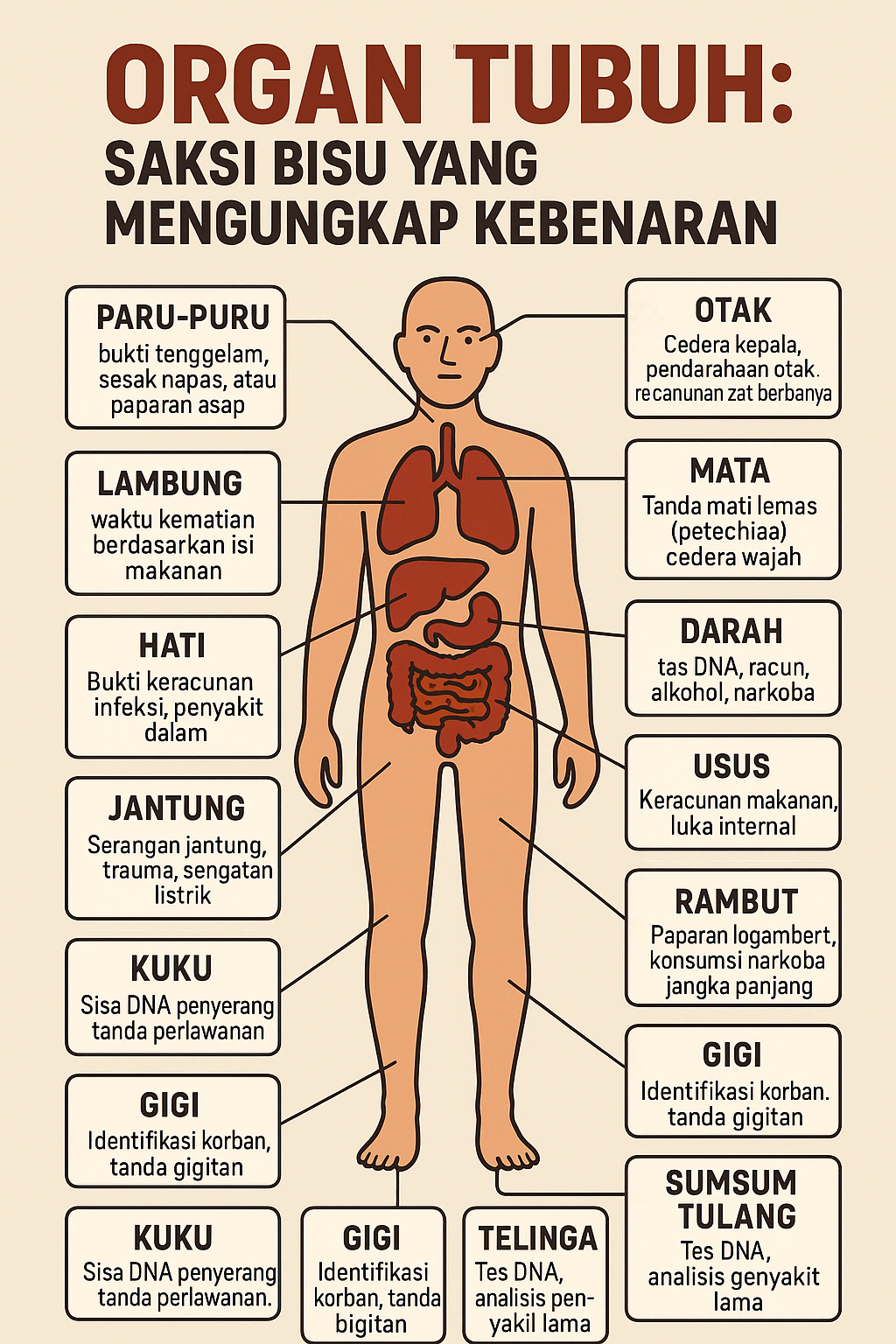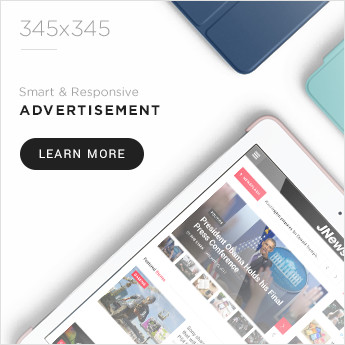Posisi-Posisi Etika yang Kini Dianggap Norak
Gareng berkata:
“Etika itu ibarat gaya misionaris dalam politik—dulu sopan, sekarang dibilang kuno.”
Zaman dahulu, etika dalam kekuasaan dijunjung tinggi. Ada norma, ada rasa malu, ada kehalusan budi. Sekarang? Etika dianggap penghalang klimaks.
Politikus berlomba-lomba mencoba posisi kuasa baru: jungkir balik janji kampanye, split semangat rakyat, doggy-style reformasi palsu. Semua demi kenikmatan instan, bukan keberlanjutan kebaikan.
G-Spot Demokrasi Sudah Mati Rasa
Dulu, suara rakyat adalah titik gairah demokrasi. Tapi sekarang, G-spot itu mati rasa—dipencet berkali-kali tak ada efek, karena sudah kebas oleh pengkhianatan demi pengkhianatan.
Pemilu jadi foreplay penuh pura-pura: rayuan manis, poster mesra, dan panggilan “saudaraku” yang berubah jadi “rakyat kecil” begitu menang.
Mereka bilang: “Saya dari rakyat!”
Tapi hidupnya lebih mirip raja pesta daripada pelayan negara.
Skandal Etika dan Hubungan Terlarang dengan Uang
Etika hari ini diselingkuhi oleh uang dan kuasa.
Anggaran dijadikan simpanan gelap. Proyek-proyek diobral untuk keluarga, kolega, dan teman tidur politik. Dan ketika ketahuan, mereka berdalih: “Saya difitnah. Ini bagian dari skenario besar.”
Kata Petruk, “Kalau korupsi itu zina, maka mereka adalah pezina berjamaah yang rajin khatamkan APBN.”
Cinta Satu Malam Bernama Jabatan
Jabatan sekarang ibarat cinta satu malam. Begitu dapat, langsung dinikmati, disedot keuntungannya, lalu ditinggal ketika hamil masalah.
Tak ada tanggung jawab, tak ada cinta. Hanya seks politik semalam suntuk, penuh kenikmatan di atas penderitaan rakyat.
Rakyat Sebagai Objek Fantasi, Bukan Subjek Cinta
Rakyat tak lebih dari fantasi kampanye. Muncul di baliho, hilang di APBD. Mereka dibujuk, dirayu, dipuaskan dengan slogan, tapi setelahnya hanya jadi statistik.
“Rakyat cuma jadi background saat foto dilantik,” kata Gareng. “Setelah itu? Kembali jadi hiasan penderitaan.”
Posisi Etika Terakhir—Menjaga Diri Saat Semua Ingin Telanjang
Di tengah kekuasaan yang telanjang moral, etika adalah satu-satunya kain penutup yang tersisa.
Tapi, siapa yang mau pakai? Wong kain itu dianggap kampungan. Dianggap menghalangi gerakan “maju cepat” dan “gas pol tanpa rem”.
Jangankan Orgasme Keadilan, Ciuman Nurani Pun Kini Langka
Kita hidup di zaman ketika suara rakyat dianggap angin, etika dianggap hambatan, dan kepuasan penguasa lebih penting dari keadilan sosial.
“Kamasutra Etika”, kata Petruk, “adalah kitab yang dibaca oleh sedikit orang, dan diamalkan oleh lebih sedikit lagi.”
Gareng dan Petruk menutup kitab sambil menyeduh kopi pahit:
“Etika itu memang tidak seksi. Tapi tanpa etika, kekuasaan itu seperti seks tanpa persetujuan—menjadi pemerkosaan publik.”