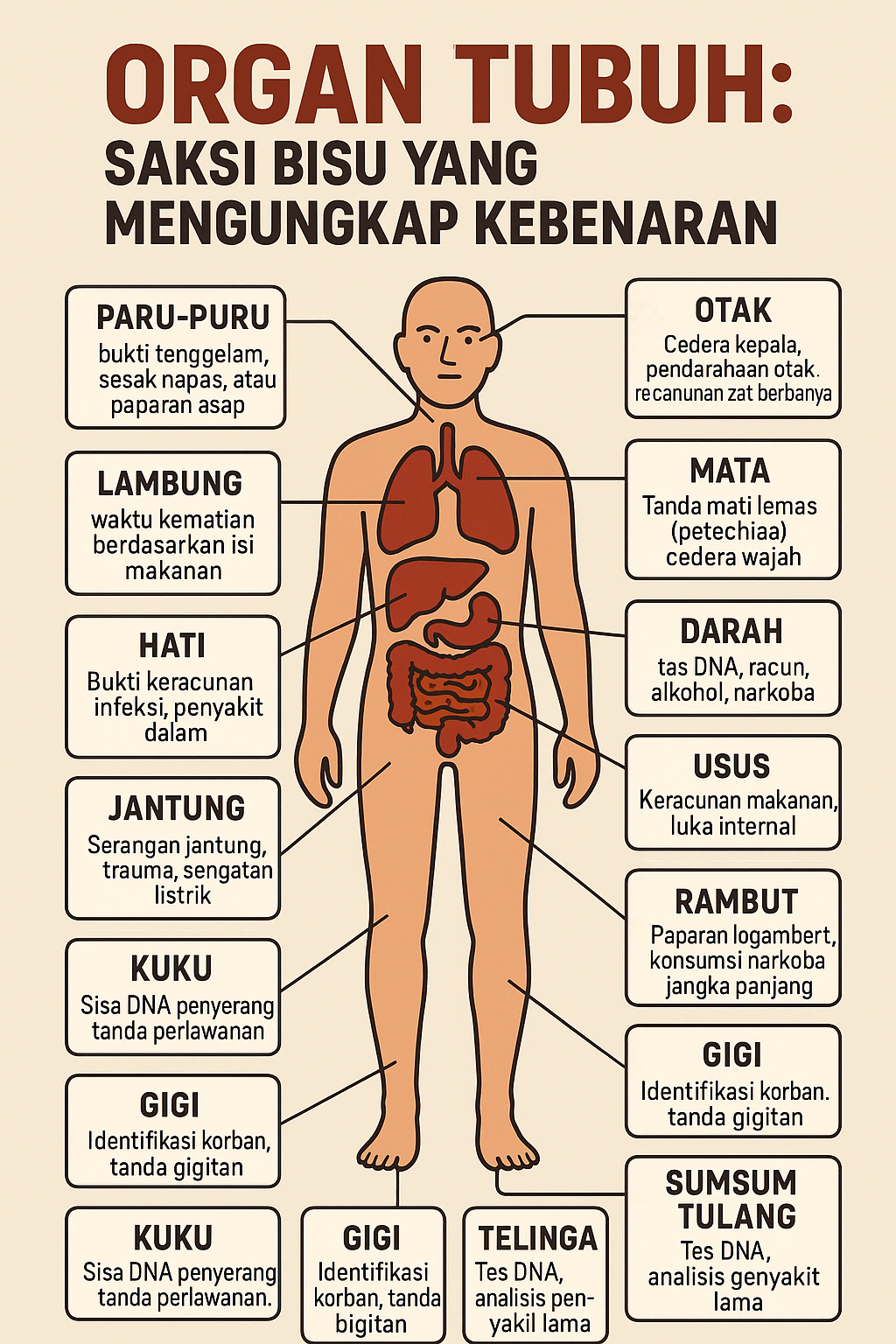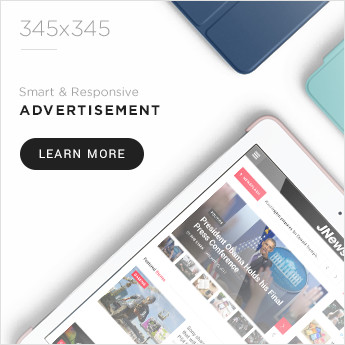SURABAYA, 13 Mei 2025 – Malam itu Balai Pemuda Surabaya bukan sekadar bangunan tua yang nganggur. Ia berubah jadi panggung kemerdekaan rasa, suara, dan estetika yang kadang kasar tapi selalu jujur. Forum Pegiat Kesenian Surabaya (FPKS) turun gunung. Dan bukan sembarang turun, tapi dengan gaya: nyeniman ala Arek Suroboyo—gaya blak-blakan, sarkas tapi ramah, dan tentu, ora ilok yen gak misuh sak dikit!
Malam bertema ‘Surabaya Hari Ini’ itu seperti reuni batin antara generasi tua-tua keladi dan milenial merangkak melek budaya. Musik, puisi, monolog—semuanya dioplos jadi satu seperti kopi sachet 3 in 1. Bedanya, ini bukan sekadar untuk nyegerin mata, tapi untuk nyadarin kepala: kita ini Surabaya, Rek!
Dari Dresscode Hitam Sampai Blak-blakan Misuh
Acara dibuka dengan anak-anak milenial binaan Heru Prastyono alias Post Ensemble. Mereka tampil dalam dresscode hitam, bukan karena duka, tapi karena hujan sore bikin suasana adem-adem syahdu. Tapi jangan salah, begitu panggung dibuka, suasana langsung padhang mbreh! Pardi Partin, Profesor Rubi Castubi, dan B. Jon tampil nggilani—nggilani dalam arti keren, lucu, dan kadang misuhnya lebih filosofis dari motivator korporat.
“Misuh kuwi budaya, asal ora ngisin-ngisini,” kata salah satu penonton sambil nyengir, nahan ketawa dan keblinger sendiri karena makna-makna nyentrik dari panggung FPKS.
Jil Kalaran: Komandan Santuy, Serius Tapi Santai
Jil Kalaran, motor utama dari acara ini, tampil sekenanya—kaos oblong, celana selutut, dan topi. Tapi dari mulut santainya, keluar kalimat sakral: “Terima kasih, Rek. Sampeyan semua bukti budaya kita masih waras meski kota makin panas.”
Dan memang, yang bikin adem itu bukan AC, tapi suasana yang terasa seperti kumpul di gang kecil belakang pasar. Akrab. Tak ada jarak. Tak ada panggung tinggi, semua sejajar—kecuali puisi yang terbang lebih tinggi dari harapan rakyat saat resesi.
Musik, Puisi, Monolog: Tiga Senjata Melawan Tumpulnya Nurani Kota
Arul Lamandau menyihir penonton lewat gesekan biola. Puisi Denting Kemuning dan Deny jadi makin dalam, seolah-olah suara senar itu adalah deru hati wong cilik yang sering dipotong suaranya oleh aturan absurd.
Heti Palestina Yunani, Tengsoe Tjahjono, dan Widodo Basuki tampil mewakili suara kaum yang lebih senang baca puisi daripada debat kusir medsos. Sedangkan Tri Wulan Purnami menyodorkan puisi ‘Binatang Jalang Bagiku’—ya, ini bukan hanya odesi untuk Chairil Anwar, tapi juga tabokan halus buat mereka yang ngaku seniman tapi sibuk endorse tanpa etos.
Dody Yan Masfa: Monolog Pedas, Kritik Pedih, Panggung jadi Mimbar
Acara ditutup dengan Dody Yan Masfa dari Teater Tobong. Ia berdiri sendiri, meneriakkan isi kepala yang selama ini cuma berani kita bisikkan dalam status WhatsApp.
> “Orang-orang tidak pernah serius dengan kebaikan! Tidak pernah sungguh-sungguh dengan kebenaran! Kita cuma main-main, memperolok zaman, memperburuknya dengan kemalasan dan kesombongan!”
Wooo… dingin langsung jadi panas! Kalimat itu bukan cuma tamparan buat penguasa yang senang tepuk tangan doang, tapi juga buat kita semua yang lupa berkarya karena sibuk bikin konten viral.
FPKS: Bukan Sekadar Forum, Tapi Alarm Budaya
Budaya Rek bukan acara satu malam. Ini awal dari gebrakan yang (semoga) konsisten. Satu bulan sekali katanya? Wah, cukup buat jadi pengingat bulanan: “Hei, Surabaya masih punya nyawa!” Tapi bukan hanya nyawa di atas panggung, tapi nyawa yang tertanam di trotoar, di pasar, di lara rakyat, dan tentu di puisi yang tak akan pernah mati.
GarengPetruk.com bilang:
Surabaya memang keras, tapi bukan berarti tak bisa berkesenian. Karena kadang, satu larik puisi lebih tajam dari 10 undang-undang yang multitafsir. Maka lanjutkan, FPKS. Bikin Balai Pemuda tak sekadar bangunan kolonial, tapi rumah kebudayaan yang tak pernah lelah berkata: “Ojo lali, Rek, nek awake dewe iso nglaras rasa, negeri iki iso luwih waras.”