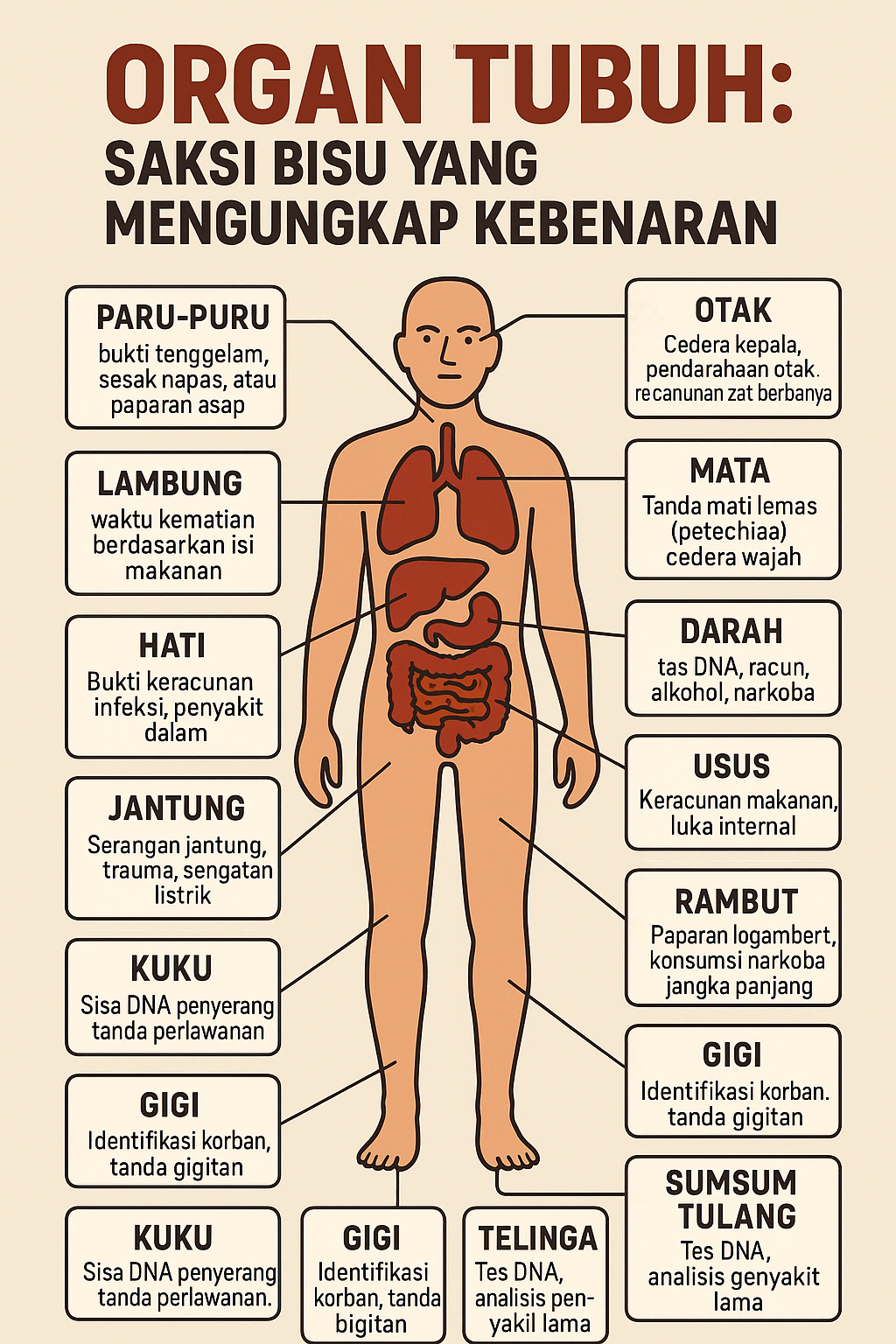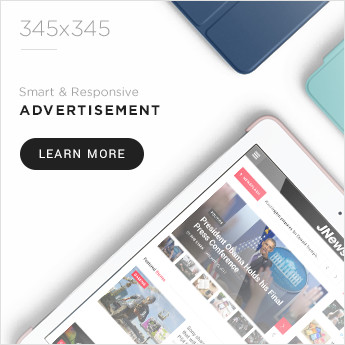Di Persimpangan Langit dan Tanah
Gareng berkata:
Seperti debu yang terbang ke langit,
Aku, engkau, kita semua, hanyalah serpihan dalam takdir semesta.
Menyusur jalan, entah kapan ujungnya tiba,
Di mana kita melangkah, di sana luka,
Namun, juga cinta, tumbuh di antara retak-retak jiwa.
Apakah engkau masih bertanya, wahai kawan,
Siapakah kita, selain debu yang ditabur ke angkasa?
Petruk menjawab:
Angin berbisik, tapi telinga kita tuli,
Padahal, jawabannya ada di senyapnya malam yang dilipat bintang.
Kita berpacu mengejar takhta dan harapan palsu,
Meninggalkan hati di belakang, terbakar oleh ambisi.
Tidakkah kau tahu, langit tak pernah memandang,
Apakah kita raja, atau hanya wayang yang melayang,
Semua adalah lakon yang telah tertulis di kelopak embun pagi.

Gareng dan Petruk bersama:
Dalam senyum sang waktu, kita pun tenggelam,
Menari di panggung yang tak pernah bertanya,
Apakah cinta itu masih setia,
Ataukah hanyalah mimpi yang usang,
Seperti daun yang gugur, terhanyut air,
Begitulah kita, sahabat, terhisap oleh derasnya arus zaman.
Maka, sebelum langit menutup tirainya,
Mari kita menundukkan kepala,
Bukan kepada raja atau pangeran,
Tapi pada hati kita yang lelah namun terus percaya,
Bahwa esok adalah hari di mana kita kembali,
Bukan untuk menang,
Tapi untuk menjadi lebih manusia.
Di akhir bisikan ini, Petruk pun terisak:
“Selamat tinggal, wahai mimpi yang tak pernah nyata,
Namun biarlah, di dalam dada,
Aku masih bisa merasakan hangatnya cinta.”
Gareng menghela nafas panjang:
“Dan biarlah air mata ini jatuh,
Bukan karena pedih,
Tapi karena akhirnya kita paham,
Bahwa perjalanan ini, meski berliku, adalah pelajaran abadi,
Dan kita, walau hanya bayang-bayang di atas panggung,
Tetaplah bagian dari keajaiban semesta yang menari dalam sunyi.”