Sumpah Pemuda yang Sudah Beranjak Tua: Masihkah Kita Setia pada Tanah, Air, dan Bahasa Indonesia?
Ada yang menua, tapi bukan usia. Ada yang lapuk, tapi bukan kayu.
Itulah Sumpah Pemuda — janji suci yang dulu lahir dari dada para pemuda yang matanya menyala, darahnya menyala, dan mimpinya menembus langit penjajahan. Kini, ia berdiri renta di tengah arus zaman yang deras, di antara bisingnya kepentingan dan bisu-nya nurani bangsa.
Dulu, ketika 28 Oktober disebut, dada bergetar.
Kita mengenang mereka yang bersumpah dengan segenap jiwa:
Bertumpah darah satu, tanah air Indonesia.
Berbangsa satu, bangsa Indonesia.
Berbahasa satu, bahasa Indonesia.
Tiga kalimat itu bukan sekadar seruan. Ia doa, ia janji, ia pengorbanan.
Namun kini — di usia senjanya — Sumpah Pemuda berdiri sendirian, menatap anak cucu yang tak lagi memegang tangannya.
Sumpah yang Tak Lagi Suci
Kini, sumpah itu tidak lagi dihafal dengan hati, melainkan hanya dibaca di atas podium — seperti mantra kosong yang kehilangan ruhnya.
Pemuda kini lebih sibuk memperdebatkan siapa paling nasionalis, ketimbang menjaga persatuan itu sendiri.
Bahasa Indonesia yang dulu dijunjung tinggi, kini dikalahkan oleh gengsi bahasa asing.
Tanah air yang dulu dijaga dengan darah, kini dijual dengan tanda tangan.
Bangsa yang dulu disatukan oleh derita, kini dipecah oleh ambisi.
Sumpah Pemuda kini adalah sumpah yang sulit ditepati, sumpah yang kehilangan kesucian, sumpah yang terkhianati.
Di bawah bendera merah putih yang masih berkibar, ada luka yang tak lagi diobati — luka karena lupa.
Renungan dari Hati yang Sepi
Pernahkah kita merenung, di tengah derasnya modernitas, apakah masih ada ruang di dada kita untuk Indonesia yang sederhana dan tulus?
Indonesia yang tak sibuk mencari pujian, tapi bekerja tanpa pamrih?
Indonesia yang berdiri bukan di atas kekuasaan, tapi di atas kejujuran dan cinta?
Jika dahulu pemuda berani mati demi merah putih, kini banyak yang hidup tanpa rasa malu di bawah bayangannya.
Kita bersumpah setia pada tanah air, tapi sering mengkhianatinya demi kepentingan pribadi.
Kita bersumpah satu bangsa, tapi membenci sesama anak negeri.
Kita bersumpah satu bahasa, tapi kini saling menghina dengan kata-kata yang lahir dari amarah, bukan dari cinta.
Sufisme di Tengah Luka Bangsa
Dalam sunyi, jiwa ini bertanya:
Mungkinkah sumpah itu masih suci bila tak lagi dihidupi oleh cinta?
Para sufi berkata, “Setia itu bukan di bibir, tapi di napas.”
Dan mungkin benar — sumpah itu hanya bisa hidup jika kita menghidupkannya dalam keseharian: dalam kejujuran, dalam gotong royong, dalam kesetiaan menjaga tanah ini dengan kasih, bukan ambisi.
Tanah air bukan sekadar batas peta, tapi medan spiritual tempat jiwa ini belajar arti pulang.
Bahasa Indonesia bukan sekadar alat bicara, tapi jembatan ruhani yang menyatukan ribuan hati yang berbeda.
Dan bangsa Indonesia bukan sekadar identitas di KTP, tapi perjalanan batin yang panjang menuju kemanusiaan sejati.
Sumpah yang Masih Bisa Ditebus
Meski renta, meski berdarah, meski sepi — Sumpah Pemuda belum mati.
Ia hanya menunggu generasi yang berani membasuhnya dengan air mata kejujuran dan peluh pengabdian.
Ia menunggu pemuda yang tak hanya lantang di mikrofon, tapi juga berani jujur di kehidupan nyata.
Ia menunggu mereka yang mau bersujud dalam sunyi, lalu bangkit membawa cahaya.
Karena setia pada Indonesia bukan sekadar mengenang sejarah,
tapi meneruskan nyala api yang diwariskan — bukan dengan bicara, tapi dengan berbuat.
Dan kelak, jika suatu hari negeri ini kembali merunduk karena keletihan, biarlah kita yang menegakkannya — bukan dengan sumpah di bibir, tapi dengan cinta di dada.
Karena Indonesia tak butuh sumpah yang diucapkan,
Indonesia butuh kesetiaan yang dijalankan. 🇮🇩











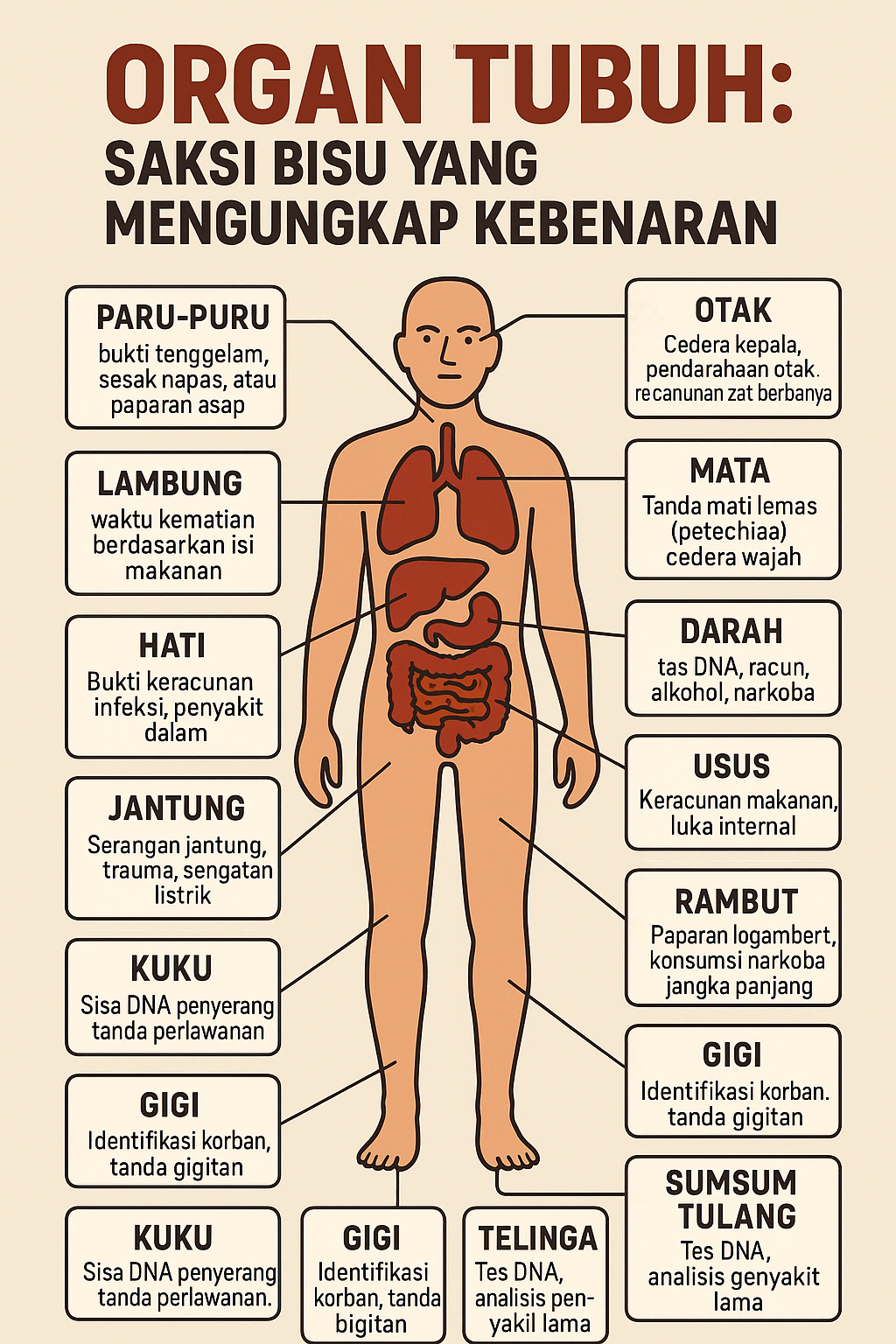



![[OPINI PUBLIK – GARENG PETRUK STYLE] “PDAM, DPRD, dan Gala-Gala di Pipa Bocor: Jangan Biarkan Air Mengalir Tanpa Pengawasan!”](https://garengpetruk.com/wp-content/uploads/2025/05/IMG-20250528-WA0013.jpg)

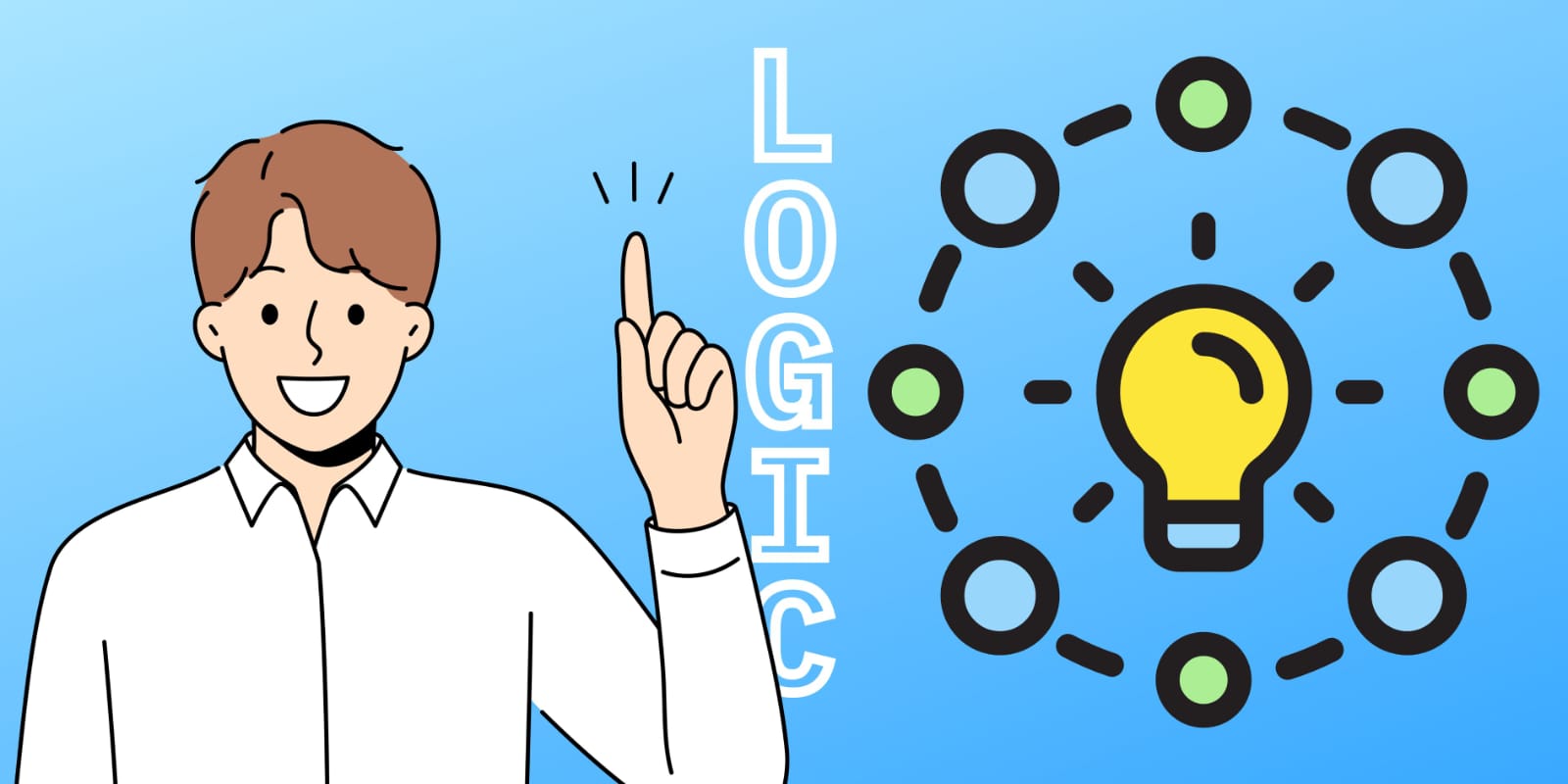

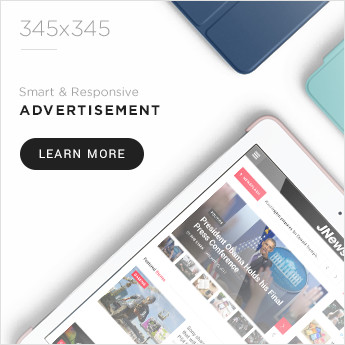

https://shorturl.fm/8g4pl