Warung kopi itu berdiri miring, berdinding bambu, beratap seng berkarat. Di dalamnya, bau kopi tubruk menyatu dengan bau hujan dan keringat lelaki-lelaki yang hidupnya tak banyak dipuji, tapi selalu berjuang tanpa jeda.
Di pojok warung, duduk tiga orang bapak.
Ada Paidi, sopir ojek yang motornya sering ngadat.
Ada Warto, buruh bangunan yang kakinya sudah kapalan tapi tetap bekerja meski demam.
Dan ada Man, tukang tambal ban yang sering menambal hatinya sendiri.
Mereka bertiga memandangi hujan sore itu, dengan mata kosong tapi hati penuh kenangan.
“Anakku kirim pesan semalam,” kata Warto pelan, mengaduk kopi tanpa arah.
“Katanya, ‘Pak, jangan nelpon terus, malu sama teman-teman. HP Bapak suaranya jelek.’”
Ia tersenyum getir, tapi suaranya serak.
“Aku cuma pengin tahu kabarnya. Katanya dia sibuk kuliah. Aku pengin denger suaranya aja. Tapi ya… mungkin HP-ku udah terlalu jadul buat dia.”
Paidi menarik napas panjang. “Aku malah udah lupa kapan terakhir anakku manggil aku ‘Ayah’. Sekarang panggilanku ‘Pak’. Kalau minta uang, baru inget nomorku.”
Man menyahut lirih, “Aku kemarin ulang tahun. Istriku gak inget, anakku juga gak. Aku cuma tiup lilin dari korek api pas ngerokok di depan rumah. Tapi aku senang… setidaknya aku masih bisa ngerokok.”
Ketiganya tertawa kecil — tawa yang lebih mirip tangis yang malu-malu keluar.
Di ujung meja, seorang lelaki tua yang sejak tadi diam akhirnya bicara.
Kakek itu memakai sarung kumal dan peci putih. Wajahnya keriput, tapi sorot matanya seperti sumur yang dalam: hitam, tenang, tapi menyimpan rahasia hidup yang pahit.
“Lelaki itu,” katanya pelan, “selalu punya cara untuk menangis tanpa air mata.”
Ketiganya menatap heran.
“Dulu,” lanjut sang kakek, “aku juga pernah seperti kalian. Aku kerja siang malam. Tak peduli dompetku tipis, yang penting dompet istri dan anak-anakku tebal. Tak apa bajuku cuma dua pasang, yang penting mereka bisa pakai baju baru setiap Lebaran. Aku berhenti merokok, bukan karena takut mati, tapi karena ingin asap dapur tetap ngebul. Aku tahan lapar, asal mereka bisa jajan di sekolah.”
Kakek itu menatap hujan yang jatuh makin deras.
“Tapi suatu hari, waktu aku pulang, rumahku sepi. Anakku sudah pergi kerja ke kota, istriku ikut cucunya di luar negeri. Aku tinggal sendiri. Mereka bilang, ‘Bapak istirahat aja di kampung, biar kami yang cari uang sekarang.’ Tapi mereka lupa, yang tua ini bukan butuh uang… yang dia butuh cuma kabar.”
Air mata Paidi jatuh pertama kali.
Ia menunduk, menutup wajah dengan tangan. Warto pun ikut menangis. Hujan di luar seolah menambah deras hujan di dada mereka.
Kakek itu melanjutkan dengan suara yang nyaris bergetar,
“Waktu aku jatuh sakit, aku baring sendiri. Aku pengin denger satu suara. Suara anakku. Aku pengin ada yang bilang, ‘Ayah, istirahat dulu.’ Tapi gak ada. Yang datang cuma suara detak jam dan tikus di atap.”
Ia menatap jauh ke luar warung, lalu tersenyum pahit.
“Dan waktu aku dipanggil Tuhan, aku gak nyesel. Aku cuma takut… anak-anakku baru sadar aku ada setelah aku gak ada.”
Paidi menatap kakek itu, air matanya belum berhenti.
“Kek… judul kisah ini kenapa ‘Jangan Panggil Aku Ayah’?”
Kakek itu tersenyum, senyum yang lembut tapi menyayat.
“Karena panggilan ‘Ayah’ sekarang sering dipakai hanya kalau butuh sesuatu. Kalau mau uang sekolah, mau pulsa, mau dibelikan sesuatu. Tapi jarang yang memanggil karena rindu. Jarang yang memeluk hanya untuk bilang terima kasih.”
Ia berdiri pelan, menatap tiga bapak itu satu per satu.
“Jangan panggil aku Ayah kalau hanya mau meminta. Panggil aku Ayah kalau kau siap mencintai tanpa syarat, seperti dulu aku mencintaimu tanpa hitung-hitungan.”
Hujan reda.
Kakek itu melangkah keluar dari warung kopi, meninggalkan jejak kaki di tanah basah. Tapi saat Paidi menoleh ke arah pintu, sosok kakek itu sudah tak ada.
Yang tersisa hanya selembar uang lima ribuan di meja, dan secangkir kopi yang kini dingin — persis seperti kehidupan mereka: sederhana, pahit, tapi tetap setia menemani.
Malamnya, Paidi pulang ke rumah.
Anak-anaknya sedang sibuk dengan ponsel, istrinya sedang menonton drama Korea.
Ia duduk di teras, sendirian. Lalu ia melihat foto keluarganya di dompet lusuhnya.
Ia usap perlahan foto itu, dan berbisik pelan,
“Nak… kalau nanti Bapak gak ada, jangan cari uang Bapak.
Carilah doa Bapak. Karena itu yang selama ini menjaga langkah kalian.”
Ia tersenyum pelan, lalu menatap langit malam.
Air matanya jatuh tanpa suara.
Dan entah kenapa, malam itu bulan tampak lebih pucat dari biasanya —
seolah ia pun sedang menangis untuk semua ayah yang selalu ada,
tapi tak pernah benar-benar dianggap ada.
Epilog:
Jika engkau membaca ini sekarang,
dan ayahmu masih hidup,
peluklah dia.
Ucapkan terima kasih, walau cuma satu kalimat.
Karena mungkin… itu kalimat yang sudah ia tunggu seumur hidupnya.
Dan bila ayahmu telah pergi,
maka tenangkan hatimu, sebab di alam sana,
ia tetap berdoa:
“Tuhanku, bahagiakanlah anak-anakku, walau mereka sering lupa padaku.”











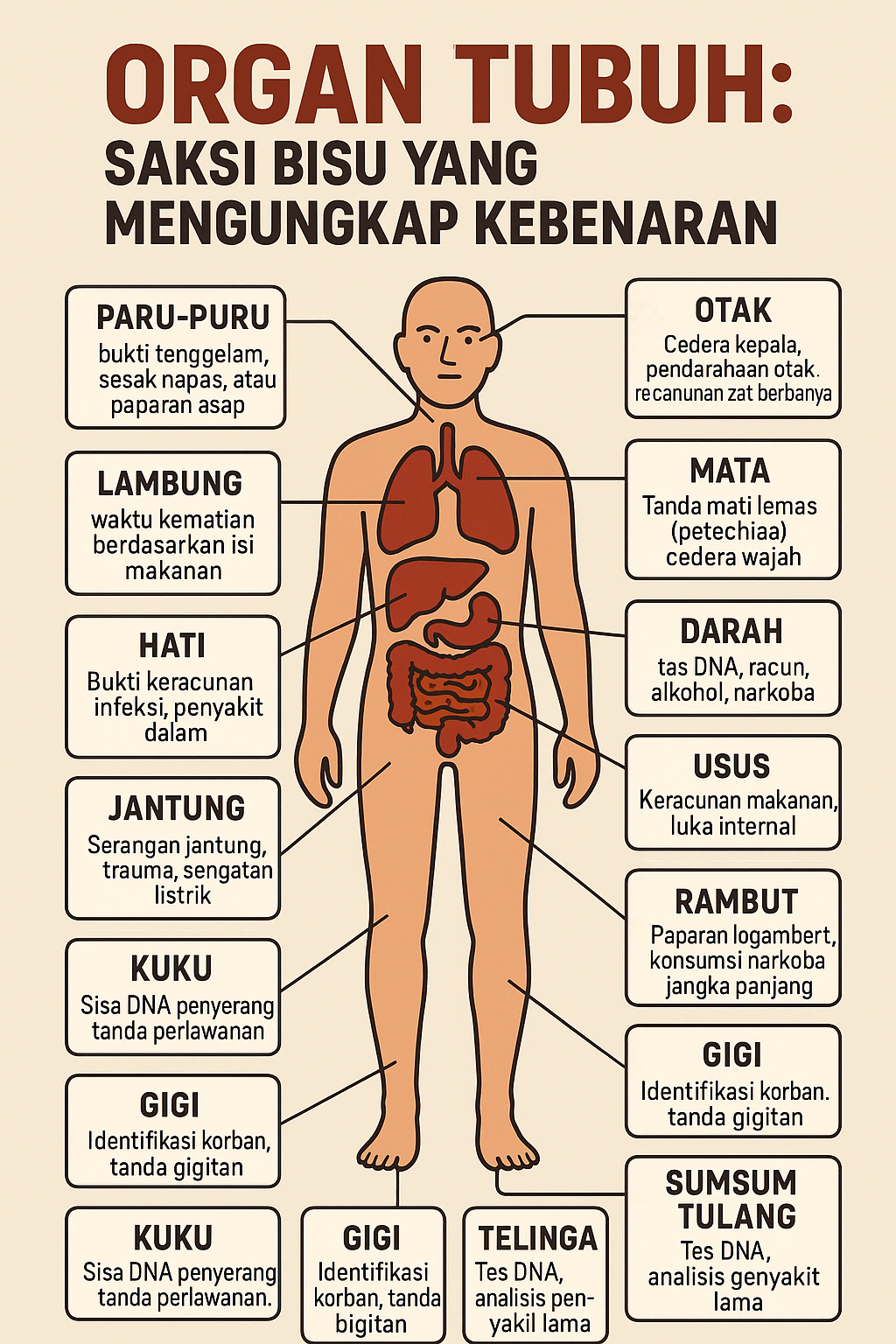







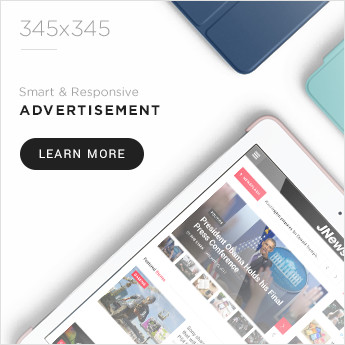

https://shorturl.fm/wlh6y